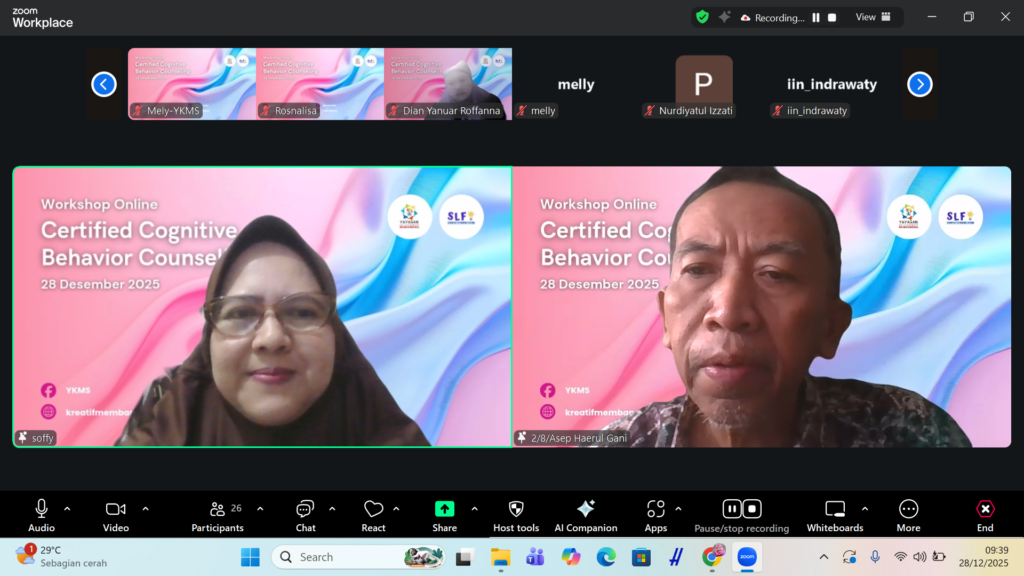Kendali Diri dalam Masyarakat Komunal: Tantangan Konseling pada Klien Indonesia Melalui CBT
Salah satu tema yang paling sering muncul dalam Praktik konseling dan pendampingan psikologis, adalah keluhan klien tentang hidup yang terasa “berantakan”, tidak adil, dan penuh tekanan. Menariknya, ketika ditelusuri lebih dalam, banyak dari permasalahan tersebut bersumber dari hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali diri klien. Namun, alih-alih menerima keterbatasan kendali tersebut, klien justru menghabiskan energi emosional dan kognitifnya untuk memikirkan, memperdebatkan, dan melawan kenyataan yang tidak dapat ia ubah. Di sinilah pentingnya pertanyaan fundamental dalam proses konseling: “Apakah ini berada dalam kendali saya atau tidak?”
Konsep pemisahan antara hal yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan menjadi fondasi penting dalam regulasi emosi dan problem solving. Banyak klien terjebak dalam penderitaan bukan semata karena peristiwa yang dialami, tetapi karena cara mereka memaknai dan merespons peristiwa tersebut. Ketika seseorang terus-menerus berusaha mengendalikan sesuatu yang di luar kendalinya—misalnya sikap orang lain, masa lalu, kondisi ekonomi global, atau penilaian sosial—maka frustrasi dan kecemasan hampir pasti muncul.
Dalam pendekatan Acceptance and Commitment Therapy (ACT), dikenal konsep defusion, yaitu kemampuan untuk mengambil jarak dari pikiran. Defusion bukan berarti menghilangkan pikiran negatif, melainkan membolehkan pikiran muncul tanpa harus mempercayainya sepenuhnya atau dikendalikan olehnya. Klien diajak menerima kenyataan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol, dan penerimaan ini bukan bentuk menyerah, melainkan bentuk kebijaksanaan psikologis. Ketika seseorang berkata, “Saya tidak bisa mengontrol ini,” maka langkah selanjutnya bukan menghindar, melainkan bertanya, “Lalu apa yang masih bisa saya lakukan?”
Penerimaan (acceptance) sering kali disalahartikan sebagai pasrah. Padahal, dalam konteks psikologis, penerimaan justru membuka ruang untuk fokus pada area yang masih berada dalam kendali. Ciri-ciri sesuatu yang berada dalam kendali diri antara lain: adanya keinginan untuk berubah, kemauan untuk belajar keterampilan baru, kemampuan mengelola respons emosi, serta sumber daya yang realistis seperti waktu, energi, dan dalam beberapa kasus, kondisi finansial. Misalnya, seseorang tidak dapat mengontrol keputusan perusahaan untuk melakukan PHK, tetapi ia masih dapat mengontrol bagaimana ia mempersiapkan diri, meningkatkan keterampilan, atau mengatur ulang rencana hidupnya.
Salah satu teknik yang efektif untuk membantu klien memahami batas kendali ini adalah behavior experiment. Klien diajak membayangkan dua skenario: pertama, situasi yang sepenuhnya berada di luar kendali; kedua, situasi yang masih berada dalam kendali diri. Melalui eksperimen mental ini, klien dapat merasakan perbedaan emosional antara terus-menerus melawan realitas versus mengalihkan energi pada tindakan yang bermakna. Sering kali, klien menyadari bahwa kelelahan emosional mereka berasal dari perjuangan yang sia-sia.
Dalam konteks Indonesia, dinamika ini menjadi lebih kompleks karena budaya masyarakat yang bersifat komunal. Individu tidak hanya dipandang sebagai pribadi otonom, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga, komunitas, dan norma sosial. Banyak klien merasa tertekan karena tuntutan untuk selalu peduli, menyesuaikan diri, dan mengorbankan kepentingan pribadi demi harmoni kelompok. Akibatnya, batas antara “tanggung jawab pribadi” dan “tanggung jawab kolektif” menjadi kabur. Klien sering memikul beban emosional atas masalah yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya.
Dalam CBT, masalah klien tidak dilihat semata-mata berasal dari budaya komunal itu sendiri, melainkan dari pola pikir (cognitive appraisal) dan pola perilaku (behavioral response) klien dalam merespons tuntutan sosial. Oleh karena itu, intervensi difokuskan pada restrukturisasi kognitif, klarifikasi tanggung jawab, dan eksperimen perilaku.
Kondisi ini dapat memunculkan apa yang disebut sebagai perceptual problem, yaitu masalah yang terus diperdebatkan tetapi tidak pernah benar-benar selesai. Contohnya, konflik keluarga yang berulang, perasaan tidak dihargai, atau tuntutan sosial yang saling bertentangan. Masalah ini sering kali bukan karena kurangnya solusi, tetapi karena persepsi yang saling berbenturan dan tidak dapat dikontrol oleh satu pihak saja. Ketika klien terus berusaha “menyelesaikan” masalah yang bersifat perceptual tanpa mengubah cara pandang, maka kelelahan psikologis menjadi tak terhindarkan.
Di sinilah relevansi pemikiran Salvatore R. Maddi, tokoh psikologi yang dikenal dengan konsep hardiness dan pendekatan problem solving yang berorientasi pada makna. Maddi menekankan pentingnya regulasi emosi dan kemampuan mengalihkan fokus pada hal-hal yang masih dapat dikuasai. Menurutnya, individu yang tangguh secara psikologis tidak menolak realitas sulit, tetapi berkomitmen untuk tetap terlibat, merasa memiliki kendali (control), dan melihat tantangan sebagai peluang pembelajaran (challenge).
Pendekatan problem solution ala Maddi bukan tentang mencari solusi instan, melainkan membangun sikap mental yang adaptif. Ketika emosi dapat diregulasi dengan baik, individu memiliki ruang kognitif yang lebih luas untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan yang selaras dengan nilai hidupnya. Fokus dialihkan dari “mengapa ini terjadi pada saya?” menjadi “apa langkah kecil yang bisa saya lakukan hari ini?”
Pemahaman ini semakin kuat jika dikaitkan dengan teori Daniel Kahneman tentang dua sistem berpikir: System 1 (fast thinking) dan System 2 (slow thinking). System 1 bekerja secara otomatis, cepat, dan emosional. Dalam kondisi stres, kecemasan, atau tekanan sosial, klien cenderung didominasi oleh System 1. Mereka menggunakan jalan pintas mental, untuk menilai situasi. Akibatnya, muncul generalisasi berlebihan, asumsi negatif, dan reaksi impulsif.
Sebaliknya, System 2 bersifat reflektif, rasional, dan membutuhkan usaha. Proses membedakan antara hal yang bisa dan tidak bisa dikendalikan adalah bentuk aktivasi System 2. Klien diajak memperlambat cara berpikirnya, menantang asumsi otomatis, dan menyadari bahwa tidak semua pikiran adalah fakta. Dengan demikian, defusion menjadi jembatan antara kesadaran kognitif dan regulasi emosi.
Pada akhirnya, penderitaan psikologis sering kali bukan disebabkan oleh beratnya masalah, melainkan oleh kesalahan fokus. Ketika seseorang terus memusatkan perhatian pada hal-hal di luar kendalinya, ia kehilangan akses terhadap kekuatan internal yang sebenarnya dimiliki. Melalui penerimaan, pemisahan kendali, regulasi emosi, dan pengalihan fokus pada tindakan bermakna, klien dapat membangun kembali rasa agensi dalam hidupnya—bahkan di tengah keterbatasan dan tuntutan sosial yang kompleks.
Dalam konteks Indonesia, dinamika ini menjadi lebih kompleks karena budaya masyarakat yang bersifat komunal. Individu tidak hanya dipandang sebagai pribadi otonom, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga, komunitas, dan norma sosial. Banyak klien merasa tertekan karena tuntutan untuk selalu peduli, menyesuaikan diri, dan mengorbankan kepentingan pribadi demi harmoni kelompok. Akibatnya, batas antara “tanggung jawab pribadi” dan “tanggung jawab kolektif” menjadi kabur. Klien sering memikul beban emosional atas masalah yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya. Bagaimana solusinya?
1. Identifikasi Distorsi Kognitif yang Dipicu Budaya Komunal
Langkah awal CBT adalah membantu klien mengenali automatic thoughts yang muncul akibat tuntutan sosial. Dalam konteks Indonesia, distorsi kognitif yang sering muncul antara lain:
- Personalization
“Kalau keluarga tidak bahagia, itu salah saya.” - Should statements
“Saya harus selalu mengalah demi keluarga.” - Over-responsibility belief
“Kalau saya tidak membantu, saya anak yang tidak berbakti.” - Catastrophizing
“Kalau saya menolak, hubungan pasti rusak.”
Intervensi CBT membantu klien menuliskan pikiran otomatis tersebut dan menilai:
- Apakah pikiran ini fakta atau interpretasi?
- Apakah ini tanggung jawab saya sepenuhnya atau bersama?
2. Restrukturisasi Kognitif: Memisahkan Peran Sosial dan Beban Psikologis
CBT tidak menolak nilai kolektivisme, tetapi membantu klien menafsirkan ulang makna kepedulian secara lebih sehat.
Teknik yang digunakan:
- Socratic questioning, misalnya:
- “Apa bukti bahwa Anda harus menanggung semua ini sendirian?”
- “Jika orang lain berada di posisi Anda, apakah Anda akan menuntut hal yang sama?”
- Reframing adaptif, contohnya:
- Dari: “Saya egois jika menolak”
- Menjadi: “Menjaga batas adalah bentuk tanggung jawab pada diri sendiri dan relasi.”
Tujuan tahap ini adalah membentuk core belief baru:
Saya boleh peduli tanpa harus mengorbankan kesehatan mental saya.
3. Klarifikasi Batas Tanggung Jawab (Responsibility Pie Chart)
Teknik khas CBT yang sangat efektif dalam konteks ini adalah responsibility pie chart.
Langkah:
- Masalah dituliskan secara spesifik (misalnya konflik ekonomi keluarga).
- Klien membagi tanggung jawab ke dalam diagram lingkaran:
- Peran diri sendiri
- Peran anggota keluarga lain
- Faktor eksternal (ekonomi, sistem sosial, budaya)
- Klien melihat secara visual bahwa beban tidak sepenuhnya miliknya.
Dampak terapeutik:
- Mengurangi rasa bersalah irasional
- Mengaktifkan pemikiran rasional (System 2)
4. Behavioral Experiment: Menguji Keyakinan Sosial yang Kaku
Banyak klien meyakini bahwa menolak = hubungan rusak. CBT menguji keyakinan ini melalui eksperimen perilaku.
Contoh eksperimen:
- Klien mencoba menolak secara asertif satu permintaan kecil
- Mengamati:
- Apa yang sebenarnya terjadi?
- Apakah konsekuensinya seburuk yang dibayangkan?
Hasil yang sering muncul:
- Reaksi orang lain tidak seburuk prediksi
- Kecemasan menurun setelah perilaku dilakukan
- Klien memperoleh bukti baru yang menantang pikiran lama
5. Pelatihan Asertivitas Berbasis Budaya
CBT mengajarkan asertivitas yang kontekstual, bukan konfrontatif.
Contoh skrip asertif yang sesuai budaya Indonesia:
- “Saya ingin membantu, tapi saat ini kemampuan saya terbatas.”
- “Saya peduli, namun saya juga perlu menjaga kondisi saya.”
- “Mari kita cari solusi bersama, tidak hanya saya.”
Latihan dilakukan melalui:
- Role play
- Homework assignment
- Evaluasi pengalaman emosional setelah praktik
6. Aktivasi Perilaku: Menguatkan Peran Diri yang Seimbang
CBT membantu klien membangun kembali aktivitas yang memperkuat identitas personal, bukan hanya peran sosial.
Contoh:
- Waktu istirahat tanpa rasa bersalah
- Aktivitas pengembangan diri
- Kegiatan bermakna yang tidak terkait kewajiban keluarga
Tujuan:
- Mengurangi burnout
- Meningkatkan sense of agency
- Menyeimbangkan diri sebagai individu dan anggota kelompok
Dengan demikian, dalam pendekatan CBT, solusi terhadap tekanan budaya komunal bukan dengan menolak nilai kebersamaan, melainkan dengan mengoreksi cara berpikir yang tidak adaptif, memperjelas batas tanggung jawab, dan membangun perilaku asertif yang sehat. Dengan demikian, klien dapat tetap menjadi bagian dari komunitas tanpa kehilangan kesehatan mental dan identitas dirinya
Penyusun tulisan : Soffy Balgies & Bantuan AI
Psikolog, Akademisi dan Praktisi CBT